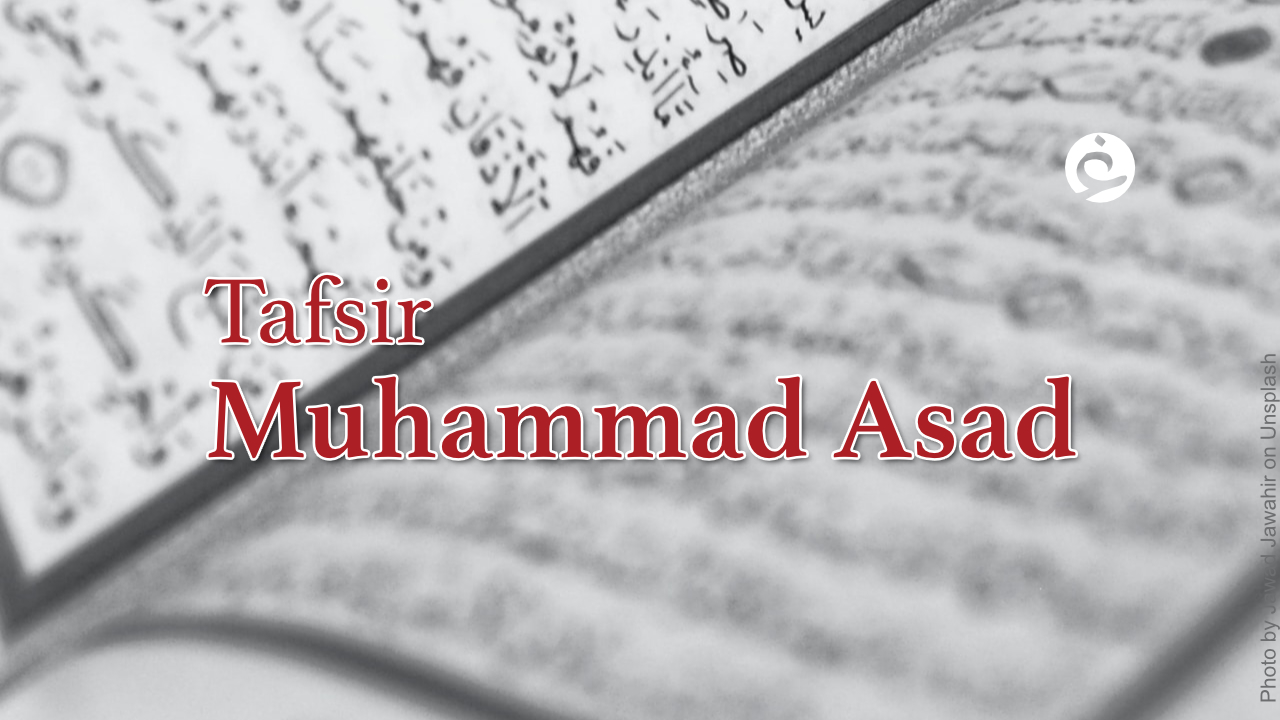Kelahiran Maryam dan Yahya
Katakanlah [wahai Nabi]: “jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, [dan] Allah akan mencintai kalian serta mengampuni dosa-dosa kalian; karena Allah Maha Pengampun, Sang Pemberi Rahmat.”
Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul.” Dan, jika mereka berpaling -perhatikanlah, Allah tidak menyukai orang-orang yang mengingkari kebenaran. [QS Alu Imran: 31-32]
Sepuluh ayat yang saya baca ini berkisah tentang kelahiran Maryam dan Yohanes Pembaptis (Yahya). Kisah tentang rasul-rasul dan nabi-nabi dalam lingkungan keluarga Daud ini dibuka dengan sebuah penegasan yang menarik dalam ayat 3:31. Ayat 3:31 menegaskan: jika kalian benar-benar cinta Tuhan, maka konsekwensinya kalian juga harus mencintai nabi-nabi Tuhan, terutama Nabi Muhammad. Kecintaan itu sesuatu yang ada dalam hati. Tak ada seorangpun yang tahu. Karena itu, cinta harus dibuktikan dengan sebuah tindakan. Bukti kecintaan pada Tuhan dan nabi-nabiNya tak lain adalah mengikuti ajaran moral yang dibawa oleh para nabi itu.
Lalu ayat 3:33 dan seterusnya berkisah tentang keluarga Imran. Karena itu surah ini disebut dengan Alu Imran; artinya keluarga Imran. Imran adalah istilah Quran untuk Amram dalam Perjanjian Lama. Amram memiliki putera/puteri berikut: Harun, Musa dan Miryam (bukan Maryam). Ayat 3:35 berbicara tentang kelahiran Maryam yang tak lain ialah ibu Nabi Isa atau Yesus. Tapi ayat ini memang mengandung sebuah kemusykilan. Di mana letak kemusykilan dalam ayat 3:35? Dan bagaimana Asad mengatasi dan menjawab kemusykilan ini? Ini pertanyaan yang menantang saya. Ayat 3:35 berkisah tentang kelahiran Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Di sana dikisahkan bahwa ibunya Maryam bernazar saat mengandung. Mari kita baca saja selengkapnya isi nazar ibunya Siti Maryam itu seperti dikisahkan dalam ayat 3:35 ini.
Dan, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui tatkala seorang perempuan dari [keluarga] ‘Imran berdoa: ‘Wahai, Pemeliharaku! Perhatikanlah, pada-Mu kunazarkan [anak] yang ada dalam kandunganku, agar mengabdi melayani-Mu. Karena itu, terimalah ia dariku: sungguh, hanya Engkau-lah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. [Alu ‘Imran: 35]
Isi nazar itu ialah: anak dikandung ibunya Siti Maryam itu akan diserahkan kepada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Pertanyaannya ialah: siapa nama ibunya Siti Maryam? Empat Injil yang dibaca umat Kristen sekarang sedikit sekali bicara soal sosok Maria/Maryam. Quran sendiri juga tak menyebutkan siapa nama ibunya Siti Maryam. Tetapi Quran memberi sedikit isyarat: bahwa dia adalah isterinya Imran. Karena itu, Quran menyebut ibunya Siti Maryam sebagai “Imra’atu Imran”, isterinya imran, atau Amram dalam istilah Perjanjian Lama. Tetapi di sini letak kemusykilannya. Tak mungkin ibunya Siti Maryam adalah isterinya Amram atau Imran. Sebab Imran adalah bapaknya Nabi Musa. Jarak antara Siti Maryam dan Nabi Musa sangat jauh. Tak mungkin isterinya Imran yang adalah ibunya Nabi Musa adalah juga ibunya Siti Maryam. Kemusyikilan ini dijadikan oleh sebagian polemikus dan apologet Kristen (baik klasik atau modern) untuk menyerang Quran.
Menurut sebagian apologet Kristen, Quran mengandung kekeliruan data sejarah, yaitu menyebut bahwa ibunya Siti Maryam dan Musa sama. Padahal antar Siti Maryam dan Nabi Musa dipisahkan oleh ratusan tahun. Bagaimana bisa ibunya Siti Maryam dan Nabi Musa sosok yang sama. Kata sebagian apologet Kristen, Quran mencampur-adukkan antara dua orang yang berbeda tapi dengan nama yang agak mirip, yaitu Maria dan Miryam. Maria atau Maryam adalah ibunya Nabi Isa/Yesus. Sementara Miryam adalah ibunya Nabi Musa. Namanya mirip, tapi orangnya beda. Inilah kata sebagian apologet Kristen. Saya kira Asad tahu tentang “kemusykilan” yang ada pada ayat 3:35 ini, yaitu terkait siapa ibunya Maryam. Bagaimana Asad mengatasi kemusykilan ini? Nah, inilah yang menarik.
Tidak seperti penerjemah-penerjemah Quran yang lain, Asad sengaja menerjemahkan frasa “imra’atu Imran” itu dengan: seorang perempuan dari (keluarga) Imran. Lalu, editor ahli Mizan, Dr. Afif Muhammad, membubuhkan catatan kaki atas terjemahan Asad ini dengan komentar berikut:
“Seorang perempuan dari [keluarga] ‘Imran” adalah terjemahan yang diberikan penyusun untuk kalimat imra’at ‘Imran. Dalam terjemahan Al-Quran Depag RI, kalimat tersebut diterjemahkan menjadi “istri ‘Imran”. Terjemahan Asad lebih sesuai dengan redaksi Al-Quran.
Dengan terjemahan seperti itu, Asad ingin menghindarkan dari kemusyiklan tadi itu. Jadi, imra’atu Imran bukan isterinya Imran. Melainkan perempuan dari keluarga Imran. Secara silsilah, memang ibunya Siti Maryam (siapapun nama dia) masih keturunan keluarga Imran/Amram.
Tetapi, sebetulnya siapa nama Ibunya Siti Maryam, alias neneknya Nabi Isa/Yesus? Bible tak menyebutkan, begitu juga Quran.
Keterangan soal ini tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Satu-satunya informasi kita jumpai dalam apa yang disebut dengan “apocryphal gospels”. Yaitu injil-injil apokrif, yakni injil yang tak diakui oleh gereja. Semacam injil “liar” yang tak dianggap sebagai injil kanonik.
Dalam injil apokrif itulah terdapat informasi bahwa ibunya Siti Maryam atau Maria bernama Anne, sementara bapaknya bernama Joachim. Membaca tafsir Asad ini menarik sekali, sebab dia berada di persimpangan antara tiga tradisi semitik yang besar: Yahudi, Kristen dan Islam. Asad mengerti benar tradisi Yahudi (sebab dia sendiri orang Yahudi yang masuk Islam), dia tahu Kristen, dan juga belajar Islam dengan serius. Tafsir Asad ini mencerminkan sosok yang memiliki kesadaran yang akut/mendalam sekali tentang tradisi tiga agama besar: Yahudi, Kristen, Islam. Karena itu, membaca tafsir Asad ini memberikan kenikmatan yang luar biasa (joy of reading). Selain terjemahan Indonesianya juga bagus sekali!
*disebut Miryam Saudari nabi Musa, anak Imran. Miryam adalah saudari Nabi Musa. Tapi Maryam (Maria) adalah ibunya Yesus/Isa. Miryam dan Maryam memang agak-agak mirip. Tapi beda orang.
Pagi ini saya masih akan membahas sepuluh ayat yang saya bahas kemaren, yaitu mengenai kisah Maryam, Zacharia, dan Yohanes Pembaptis (Yahya). Sepuluh ayat itu ada dalam bagian awal Surah Alu Imran: 3:31-40. Ayat-ayat ini menarik perhatian saya karena banyak mengisahkan tentang Maryam. Sebagaimana kita tahu, perbedaan yang mencolok antara Quran dan Injil adalah dalam hal pembahasan soal sosok Maryam, ibu dari Nabi Isa ini. Sementara Injil tak memberikan perhatian yang cukup atas sosok Maryam (atau Mary), Quran sebaliknya: memberikan perhatian yang sangat besar. Surah Alu Imran ini salah satu yang membahas soal Maryam. Tetapi ada satu surah (chapter) yang khusus membahas sosok Maryam, yaitu Surah Maryam. Di mata umat Islam, sosok Maryam ini sangat penting kedudukannya. Satu-satunya perempuan yang disebut namanya dengan jelas di Quran adalah juga Maryam.
“[Zakariya] berdoa, “Wahai, Pemeliharaku! Berikanlah suatu tanda untukku!” Berkatalah [malaikat]. “Tandanya bagimu adalah bahwa selama tiga hari engkau tidak akan bercakap-cakap dengan manusia, kecuali dengan isyarat. Dan, ingatlah Pemeliharamu dengan tiada henti, dan bertasbishlah (memuji) kemuliaan-Nya yang tak terhingga, siang dan malam.” [QS Alu ‘Imran 41]
Surah Alu Imran ini juga membahas tentang kelahiran Nabi Yahya, atau dikenal sebagai Yohanes Pembaptis di Injil (Yahya al-Ma’madani/يحيى المعمدانى). Kisah tentang kelahiran Yohanes sebagaimana dikisahkan dalam ayat: 3:38-41 di atas.
Kelahiran Nabi Yahya/Yohanes Pembaptis terjadi dengan proses yang penuh dengan keajaiban, persis dengan kelahiran Nabi Isa/Yesus. Ayah Nabi Yahya, yaitu Zakariya, sudah sepuh; sementara isterinya, yaitu Elisabet (tak disebut di Quran) adalah perempuan mandul. Saat ada undian di masyarakat Yahudi saat itu untuk memilih seorang imam yang akan mempersembahkan sesembahan, terpilihlah Zakaria jadi imam. Soal undian ini disinggung juga dalam Quran, yaitu dalam ayat 3:44. Redaksi yang dipakai Quran adalah “yulquna aqlamahum”.
Setelah Zakaria terpilih jadi imam itulah, dia mendapat kabar gembira dari malaikat bahwa dia akan dikaruniai anak sabagaimana ia impikan. Kisah kelahiran Nabi Yahya dan doa Zakaria untuk memiliki anak, dikisahkan dengan lebih detil lagi dalam Surah Maryam, surah nomor 19. Saat harapan Zakaria untuk punya anak dikabulkan, kagetlah ia. Mana mungkin? Dia sudah sepuh, isterinya mandul. Mana bisa? Lalu Zakaria meminta tanda dari Tuhan jika janji untuk punya anak itu akan tiba. Tanda itu dikiri: Zakaria tiba-tiba bisu selama beberapa waktu. Kisah tentang kelahiran Nabi Yahya bisa kita jumpai di Injil Lukas, dalam perikop “Pemberitahuan tentang Kelahiran Yohanes Pembaptis” 1:5-25.
Saya, ketika pertama kali ngaji tafsir Jalalain di pesantren dulu, dan tiba pada kisah kelahiran Yahya ini, agak kurang paham. Kenapa Zakaria tiba-tiba bisu? Dan kenapa kebisuan itu dijadikan tanda kelahiran Nabi Yahya? Maksudnya apa ini. Begitu pikir saya waktu itu. Tapi saya tidak berani bertanya kepada guru saya. Pertanyaan-pertanyaan saya saat masih di pesantren itu sekarang terjawab dengan tafsiran Asad.
Mari kita baca. Soal kebisuan Nabi Zakaria itu, Muhammad Asad punya komentar yang menarik berikut ini:
Menurut Abu Muslim (yang dikutip dan disetujui Al-Razi), Nabi Zakariya a.s. hanya diperintahkan agar tidak berbicara kepada siapa pun selama tiga hari, bukannya tiba-tiba menjadi bisu seperti yang diceritakan dalam Bibel Perjanjian Baru (Lukas 1: 20-22). Jadi, “tanda” tersebut sepenuhnya bersifat spiritual dan berupa tindakan Nabi Zakariya a.s yang menenggelamkan-diri sepenuhnya dalam doa dan kontemplasi.
Dengan komentarnya ini, Asad mencoba menghilangkan unsur “mistis” serba ajaib dalam kisah kebisuan Zakaria. Katakan saja, demistifikasi. Dalam hal ini, Asad jelas sangat dipengaruhi oleh mufassir modern yang ia kagumi, yaitu Muhammd Abduh yang punya gaya berpikir serupa. Muhammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar, juga sering melakukan “rasionalisasi” atas kisah-kisah mukjizat dalam Quran, agar jadi lebih rasional. Baik Abduh dan Muhammad Asad hidup di abad sains yang rasionalistik. Pendekatan mereka dalam menafsir Quran dipengaruhi oleh semangat zaman. Ini normal saja. Semua penafsir Quran, baik di era klasik atau modern, semua sama: dipengaruhi oleh “zeit-geist”, atau roh zaman mereka. Itulah sebabnya, setiap kita membaca kitab tafsir, apapun itu, kita harus tahu juga di era apa pengarang tafsir itu hidup dan berkarya. Dengan mengetahui era mufassir, kita bisa menelaah semangat zaman yang dominan di era itu, dan apa pengaruhnya atas mufassir tersebut. Meski saya juga menolak pandangan historisisme: yaitu bahwa seorang manusia hanya merupakan “carbon copy” saja dari sejarah di mana dia hidup. Seorang mufassir memang bisa dipengaruhi oleh semangat zaman/sejarah di mana dia hidup. Tapi jangan memutlakkan sejarah juga. Sebab seorang mufassir juga bisa melampaui sejarah, dan membentuknya. Bukan sekedar dibentuk oleh sejarah.