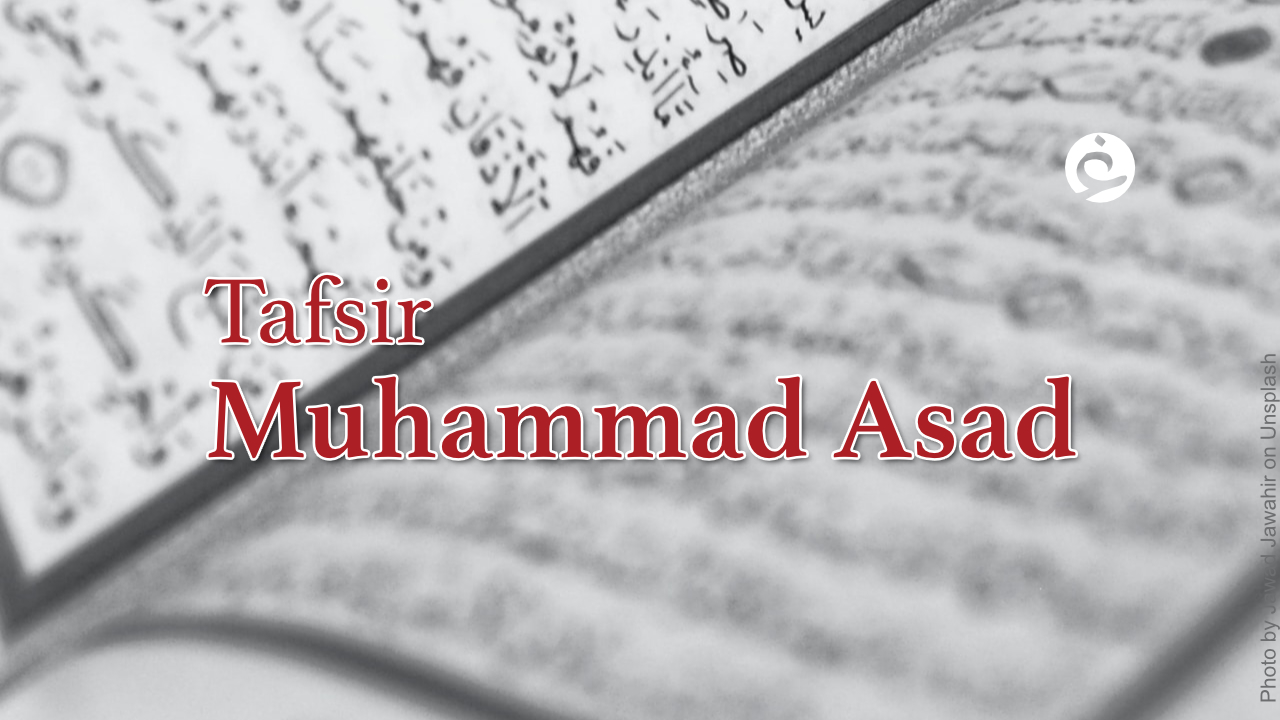Saya akan mulai dengan ayat pertama: 3:161. Ada perbedaan yang menarik antara tafsiran modern Asad dan tafsiran klasik atas ayat ini:
“Dan tidak mungkin seorang nabi menipu – karena orang yang menipu akan dihadapkan dengan tipuannya pada Hari Kebangkitan, tatkala setiap manusia akan diberi balasan sepenuhnya atas apa pun yang telah dia perbuat, dan tidak ada seorang pun yang akan dizalimi.” [Alu Imran, 3: 161]
Dalam tafsiran klasik, ayat 3:161 itu terkait dengan sebuah peristiwa pasca-Perang Badar: Nabi dituduh “ngutil” (ghulul) harta ghanimah. Ngutil, bahasa Jawa, artinya: embezzlement. Bukan sekadar mencuri. Tapi mencuri dari harta yang dipercayakan kepada kita. Nabi dituduh “ngutil” surban merah yang terbuat dari kain tenun. Dalam tafsir-tafsir klasik disebut sebagai “qathifah hamra’”.Lalu turunlah ayat 3:161 ini; ayat ini menolak tuduhan itu: tak mungkin Nabi melakukan tindakan “ghulul” (ngutil). Tapi Asad memaknai lain ayat 3:161 ini. Apa yang disebut “ghulul” bukanlah mencuri/ngutil. Tetapi: menisbhakan pendapat sendiri kepada Tuhan. Menurut Asad: ghulul artinya adalah jika seseorang mengaku-ngaku bahwa pendapat yang berasal dari dia sendiri, dia klaim sebagai berasal dari Tuhan. Mari kita baca catatan Asad mengenai ayat 3:161 ini sebagai berikut:
“Yakni, dengan menisbahkan pendapatnya sendiri kepada Allah, dan kemudian menyeru orang-orang beriman agar bersandar penuh percaya (bertawakal) hanya kepada-Nya. Betapapun penipuan semacam itu sangat tidak masuk akal, sudah menjadi pandangan umum di kalangan orang-orang kafir bahwa Nabi sendirilah yang “menyusun” Al-Quran, kemudian dengan batil menyebutnya wahyu ilahi.”
Saya agak penasaran dengan tafsiran Asad ini: seberapapun masuk akalnya tafsiran dia, apakah ada presedennya dalam tafsir klasik? Saya telusuri dalam kitab tafsir Razi (yang biasa memuat informasi yang ensiklopedik mengenai pendapat-pendapat mufasir klasik), tapi tidak saya temukan tafsiran ala Asad itu.
Tafsiran Asad yang beda ini saya coba pahami dengan menelisik makna kata “ghulul” dalam kamus-kamus Arab. Memang ada dua makna yang beda untuk kata ini.
Ada dua makna untuk kata “ghulul”: yaitu “ngutil” dan “berkhianat”. Ini bisa dibaca, misalnya, dalam kamus Munjid. Di kamus tersebut, kata “ghulul” bermakna: as-syai’u, akhadzahu fi khufyatin wadassahu fi mata’ihi.
Jika kata “ghulul” dimengerti dalam makna pertama (ngutil), maka ayat ini berkenaan dengan tuduhan bahwa Nabi mencuri harta ghanimah tadi. Tetapi jika kata “ghulul” dimaknai dalam pengertian yang kedua, maka tafsiran Asad sangat masuk akal. Ghulul dimaknai sebagai “pengkhianatan”. Jika kata “ghulul” dimaknai sebagai “pengkhianatan”, maka makna ayat 3:161 adalah: Nabi tak mungkin berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Maksud pengkhianatan di sini adalah seperti dikatakan Asad: mendaku-daku bahwa sesuatu yang berasal dari diri Nabi sendiri sebagai berasal dari Allah. Dengan kata lain, walau tafsiran Asad ini tak ada presedennya dalam tafsir klasik, tapi bisa dipahami jika dilihat dalam konteks kebahasaan. Tafsiran Asad ini sekaligus menunjukkan bahwa Asad tak sekedar mengikuti saja pendapat ulama klasik, tapi bisa juga datang dengan pendapat baru. Dengan demikian, Asad membawa pendapat dan tafsiran yang orisinal. Dan ini yang membuat tafsir The Message ini menjadi spesial dan unik.
Ayat-ayat berikutnya masih menggaungkan peristiwa Perang Uhud yang memang meninggalkan “luka traumatis” pada sahabat karena nyaris kalah. Ayat 3:165, misalnya, berisi semacam refleksi tentang kekalahan dalam Perang Uhud. Mari kita baca ayat ini selengkapnya:
“Dan, apakah kalian – ketika musibah menimpa kalian, padahal sebelumnya kalian menimpakan (musibah) yang dua kali lipat besarnya [kepada musuh-musuh kalian] – bertanya kepada diri sendiri, “Bagiamana ini bisa terjadi?” Katakanlah: “Itu berasal dari diri kalian sendiri.” [QS Alu Imran, 3: 165]
Ayat 3:165 kira-kira hendak mengatakan ini: Jika kamu kalah dalam Perang Uhud, toh kamu menang dua kali lipat dalam Perang Badar. Jadi, santai saja. Yang tertarik dengan aspek leksikografis (aspek perkamusan), ayat 3:165 ini mengandung informasi menarik terkait kata “ashabatkum musibah”.
Ada dua ungkapan yang berbeda di sini: ashabatkum mushibatun, dan ashabtum mushibatan: أصابتكم مصيبةٌ أصبتم مصيبةًYang pertama artinya: Kalian terkena musibah. Yang kedua artinya: Kalian menimpakan musibah kepada orang lain. Sekilas, kalimat: Ashabtum mushibatan bisa juga bermakna: Kalian terkena musibah, sama dengan kalimat: Ashabatkum musibatun. Tapi ternyata beda. Intrikasi atau kerumitan linguistik semacam ini tak akan nampak kalau kita hanya baca Quran dari terjemahannya saja. Kita akan bisa menangkap intrikasi dan kerumitan linguistik, sekaligus keindahan kelezatannya, jika kita baca Quran dalam bahasa aslinya.