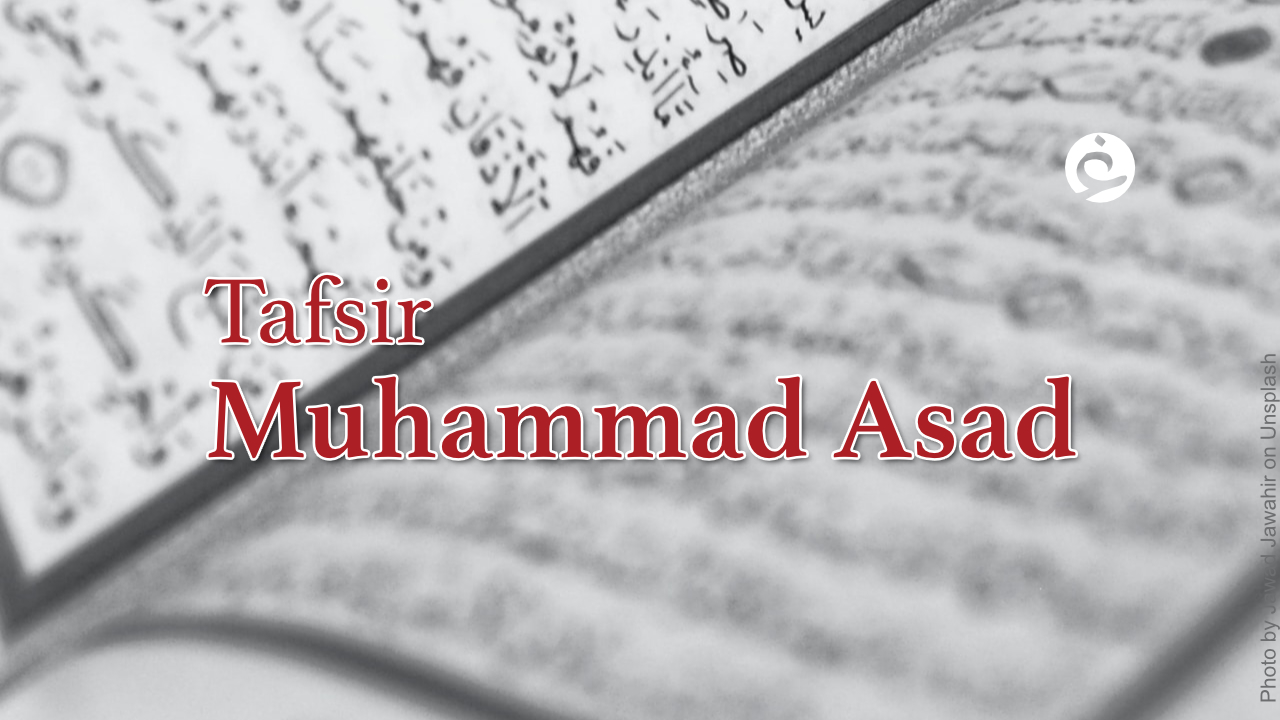“DAN, MEREKA mendaku, “Tak seorang pun akan masuk surga, kecuali orang Yahudi” -atau “orang Nasrani”. Demikianlah khayalan mereka. Katakanlah:”Tunjukkanlah suatu bukti atas pernyataan kalian itu, jika yang kalian katakan itu benar!” Tidak, sungguh: siapa pun yang menyerahkan sepenuh dirinya kepada Allah, dan juga berbuat baik, akan memperoleh ganjaran di sisi Pemeliharannya; orang-orang seperti ini tidak perlu takut, dan tidak pula akan bersedih hati.” [QS Al-Baqarah: 111-112]
Dua ayat tadi (2:111-112) adalah kritik pada sikap keagamaan bangsa Yahudi yang menganggap keselamatan hanya milik mereka saja. Sikap seperti itu sama saja dengan menganggap bahwa kebenaran dan keselamatan hanya milik kelompok sendiri. Sikap orang Yahudi ini dikritik Quran. Quran mengkritik sikap orang Yahudi ini sembari mengajarkan hal lain yang lebih terbuka: keselamatan bukan milik agama/umat tertentu. Asad menuliskan tafsirnya atas ayat 2:112 seperti berikut ini:
“Jadi, menurut Al-Quran, keselamatan itu tidak hanya dikhususkan bagi “umat” tertentu, tetapi juga terbuka bagi siapa saja yang secara sadar menyadari keesaan Allah, menyerahkan dirinya kepada kehendak-Nya, dan mewujudkan sikap spiritual ini dengan menjalani hidup secara saleh.”
Keselamatan, kata Asad, “terbuka bagi siapa saja yang secara sadar menyadari keesaan Allah, menyerahkan dirinya kepada kehendak-Nya serta mewujudkan sikap spiritual ini dengan menjalani hidup secara saleh.” Pandangan ekumenis Asad ini sejajar dengan pandangan ekumenis yang dibawa oleh Gereja Vatikan setelah Konsili Vatikan II pada tahun 60-an.
Karena keselamatan tidak menjadi monopoli umat tertentu, maka menghormati rumah ibadah semua umat beragama adalah keharusan sesuai QS 2:114. Mari kita ikuti tafsir Asad atas ayat 2:114. Menarik sekali. Saya kembali tuliskan di sini:
“Karena itu, adakah yang lebih zalim selain dari orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di rumah-rumah ibadah-Nya [yang mana pun] dan berusaha keras merobohkannya, [padahal] mereka itu tidak berhak masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut [kepada Allah]. Bagi mereka disediakan kenistaan di dunia ini; dan bagi mereka disediakan penderitaan yang mengerikan di akhirat”. [QS Al-Baqarah: 114]
Terhadap ayat 2:114, Asad membuat catatan dan tafsiran sebagai berikut:
“Salah satu prinsip dasar Islam adalah bahwa setiap agama yang menjadikan iman kepada Allah sebagai inti ajarannya harus memperoleh penghargaan penuh, betatapun banyak ajaran khasnya tidak kita sepakati. Karena itu, Muslim wajib menghormati dan melindungi setiap tempat ibadah yang dipersembahkan untuk Allah, baik itu masjid, gereja, maupun sinagoge. Dan setiap upaya mencegah penganut agama lain menyembah Tuhan, menurut pandangan agamanya itu sendiri, dikecam oleh Al-Quran sebagai pelanggaran. Sebuah contoh yang mencolok tentang prinsip ini terlihat dari perlakuan Nabi Muhammas Saw. terhadap utusan Nasrani Najran pada 10 H. Mereka diberi kebebasan memasuki masjid Nabi dan, dengan persetujuan penuh dari Nabi, melaksanakan ritual keagamaan mereka di dalamnya, meskipun pemujaan mereka terhadap Yesus sebagai “anak Tuhan” dan Maryam “ibu Tuhan” secara mendasar berlawanan dengan keyakinan Islam (lihat Ibn Sa’d I/84 dan seterusnya).”
Menghormati rumah ibadah umat manapun, kata Asad, adalah keharusan moral yang diajarkan Quran berdasarkan ayat 2:124 tadi. Tafsir ini sesuai dengan pemahaman Asad atas ayat sebelumnya, yaitu: 2:111. Di sana Quran mengkritik sikap keimanan parokial bangsa Yahudi. Tentu saja, sebagaimana penganut agama manapun, kerapkali umat Islam gagal memenuhi ajaran moral Kitab Suci mereka sendiri. Quran mengkritik sikap orang Yahudi yang menganggap kebenaran hanya ada di genggaman mereka (2:111). Ini adalah sikap keimanan parokial/picik. Tetapi sikap keimanan parokial ini juga bisa menjangkiti umat Islam. Atau umat manapun. Jika kita kembali kepada ajaran Quran yang sesungguhnya, sebagaimana dipahami oleh Muahammad Asad, parokialisme iman ini tak sesuai dengan Quran. Quran mengajarkan bahwa keselamatan adalah milik umat manapun, bukan hanya milik umat tertentu (Yahudi, Kristen, dan lain-lain), asal memenuhi kriteria.
Cukup menarik bahwa Muhammad Asad mendedikasikan tafsir ini “Bagi orang-orang yang berpikir” (mengutip Quran: li qawmin yatafakkarun). Pendekatan Muhammad Asad dalam tafsirnya ini memang sangat khas: mengajak umat Islam berpikir secara serius. Sebab kegiatan berpikir: salah satu ajaran penting dalam Quran. Peradaban besar Islam klasik adalah hasil dari “tafakkur” (bepikir) ini. Tak heran jika dalam tafsirnya ini, Muhammad Asad banyak menggunakan tafsir Al-Manar karya Abduh sebagai salah satu rujukan pokoknya. Muhammad Abduh, sebagaimana kita tahu, adalah ulama reformis Mesir dari abad ke-19 yang menggelolarakan pendayagunaan akal di dunia Islam. Tetapi tafsir al-Manar bukan satu-satunya rujukan Asad. Tafsir-tafsir klasik lain juga ia jadikan rujukan: Tafsir Tabari, Ibn Katsir, Zamakhsyari, dan lain-lain. Yang menarik, walau Asad banyak merujuk banyak tafsir klasik, ini tak menghalangi dia untuk mengajukan pendapatnya sendiri yang orisinal. Salah satu contoh yang baik adalah ketika Asad menafsir ayat 2:106 yang biasa dijadikan rujukan untuk konsep “nasakh” atau penghapusan hukum.
Menarik sekali bahwa Asad menolak konsep “nasakh”, yakni ayat yang satu dalam Quran dihapuskan oleh ayat yang lain. Konsep ini, bagi dia, absurd.
Saya kutipkan secara lengkap pendapat Asad soal teori “nasakh” berikut ini:
Prinsip yang ditetapkan dalam ayat ini – berkenaan dengan penggantian era/sistem religi Biblikal dengan era/sistem religi Qurani – telah menimbulkan suatu penafsiran keliru oleh banyak ulama. Kata “ayah” (“message”, pesan, risalah) yang ada dalam konteks ini juga digunakan untuk menunjukkan sebuah “ayat” Al-Quran (sebab, setiap ayat mengandung sebuah pesan). Dengan berpegang pada makna terbatas dari istilah “ayah” ini, sejumlah ulama menyimpulkan dari ayat di atas bahwa sebelum pewahyuan Al-Quran selesai, ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran telah “dibatalkan” (mansukh) sesuai perintah Allah. Terlepas dari keganjilan penafsiran ini – yang mengingatkan kita pada gambaran tentang seorang pengarang yang, setelah berpikir ulang, mengoreksi cetakan manuskripnya dengan menghapus satu bagian dan menggantinya dengan bagian lain – tidak ada satu pun hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi pernah menyebutkan suatu ayat Al-Quran “dibatalkan” (mansukh). Intinya, “doktrin pembatalan” (nasikh-mansukh) itu mencerminkan ketidakmampuan sejumlah mufasir awal untuk menyelaraskan kandungan suatu ayat tertentu dengan ayat lain: suatu kesulitan yang diatasi dengan menyatakan bahwa salah satu ayat yang dibahas tersebut telah “dibatalkan”. Prosedur yang arbitrer ini juga menjelaskan mengapa tidak ada kebulatan pendapat di antara para penganut “nasikh-mansukh” mengenai mana saja dan berapa jumlah ayat Al-Quran yang dibatalkan; dan selanjutnya, mengenai apakah pembatalan yang diduga-duga ini berarti penghapusan total atas ayat tersebut dari konteks Al-Quran, ataukah hanya suatu pembatalan perintah atau pernyataan tertentu yang terkandung di dalamnya. Singkatnya, “doktrin nasikh-mansukh” tidak memiliki dasar apa pun dalam fakta historis dan harus ditolak. Di sisi lain, kesulitan akan muncul dalam menafsirkan ayat Al-Quran di atas akan segera sirna jika istilah “ayah” dipahami – secara benar- sebagai “risalah” (pesan, message), jika kita membaca ayat ini dalam kaitannya dengan ayat sebelumnya, yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen menolak menerima setiap wahyu yang bisa menggantikan wahyu Bibel: sebab, jika dibaca begini, pembatalan (nasakh) itu mengacu pada risalah Allah sebelumnya dan bukan pada bagian mana pun dari Al-Quran itu sendiri.
Uraian Asad ini silakan diresapi. Kita bisa sepakat atau tidak dengan Asad soal nasakh ini. Poin saya: Walau Asad banyak bertunjang pada tafsir klasik, dia juga punya pendapat sendiri. Sudah semestinya sikap seorang Muslim modern yang hidup di abad ke-21 ini mengikuti model yang dicontohkan oleh Muhammad Asad ini. Sikap itu intinya: Kita tak boleh lupa pada kekayaan tradisi Islam yang kaya; tetapi ini tak berarti mengalangi kita untuk membawa pikiran baru. Contoh Muhammad Asad yang selalu merujuk pada tafsir-tafsir klasik tetapi juga kadang membawa pendapatnya sendiri yang berbeda, adalah contoh yang bagus.